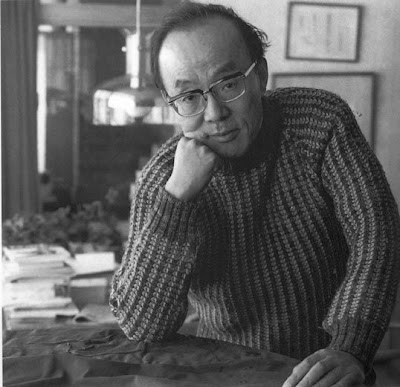“Agama adalah alat membunuh manusia yang paling berbahaya!” Sependapat atau tidak, ungkapan ini di satu sisi ada benarnya. Charles Kimball (When Religion Becomes Evil), merinci lima sebab yang membuat agama dapat berubah dari medium pembawa damai menjadi medium pembawa bencana (hal-hal yang jahat). Dalam perjalanan sejarah tradisi agama-agama, kelima hal tersebut adalah: (1) Kepatuhan buta (2) Klaim kebenaran mutlak (3) Membangun/memimpikan ‘zaman ideal’ (4) Tujuan menghalalkan segala cara, dan (5) Menyerukan perang suci.
“Agama adalah alat membunuh manusia yang paling berbahaya!” Sependapat atau tidak, ungkapan ini di satu sisi ada benarnya. Charles Kimball (When Religion Becomes Evil), merinci lima sebab yang membuat agama dapat berubah dari medium pembawa damai menjadi medium pembawa bencana (hal-hal yang jahat). Dalam perjalanan sejarah tradisi agama-agama, kelima hal tersebut adalah: (1) Kepatuhan buta (2) Klaim kebenaran mutlak (3) Membangun/memimpikan ‘zaman ideal’ (4) Tujuan menghalalkan segala cara, dan (5) Menyerukan perang suci.Semangat kebangkitan agama-agama, seiring dengan mulai surutnya kapitalisme, cenderung ‘kebablasan’. Ada yang menolak sama sekali: penggunaan rasio, akal sehat manusia, budaya lokal, hukum positif yang berlaku dalam sebuah masyarakat/negara dan tafsir ulang sesuai konteks zaman. Yang sudah dari sono-nya didedahkan pada kita begitu dari abad ke abad…ya begitu saja, terima saja, dengar saja. Tak perlu dicerna, tak perlu ditelisik, tak boleh diusik, tak boleh disanggah! Telan saja bulat-bulat! Tekstual tanpa melihat konteks. Anda tinggal terima, selamat dan masuk surga…beres bukan?! Agama-agama mulai ngecap mengklaim yang nomor satu. Merasa paling benar, paling komplet, paling sah punya kunci surga-neraka dan bahkan paling berhak ber-Tuhan serta menentukan hidup-mati orang lain. Agama-agama kadang terlalu pongah dengan ‘bahasa langit’ yang tak kait-mengkait dengan pergulatan iman manusia di bumi dalam gelombang tantangan kehidupan. Sehingga, solusi yang ditawarkan agama dirasakan umat terlalu njelimet, membingungkan, tidak praktis, tak manjur. Bahkan, kalah cepat dengan deretan problematika sekaligus ragam solusi suguhan dunia. Agama cenderung bersikap ‘alergi’ serta mengambil jarak terhadap dunia sekuler. Padahal, saat agama mewujudkan jejaknya dalam rupa rumah-rumah ibadah (Sinagoga, Gereja, Mesjid, Vihara, dsb.), ketika itulah apa-apa yang sekuler merasuki agama. Agama hanya semacam kegiatan ritual dalam keterpesonaan terhadap mujizat/hal supranatural semata. Agama bahkan terkesan nyinyir, menjadi ‘penghalang’ bagi umat manusia untuk beriman pada Sang Khalik semesta alam. Sejarah pun mencatat kekristenan – dalam institusi gereja - pernah terjebak untuk mendaku bahwa “tak ada keselamatan tanpa melalui gereja”.
Jika semua hal yang disebutkan adalah ‘label’ yang cocok disematkan pada agama saat ini, maka itu tandanya agama sedang mengalami proses pembusukan!
Alfred North Whitehead (Religion in The Making), mengingatkan agar kita tak boleh terpana oleh ide bahwa agama itu pasti baik. Sebuah ilusi yang berbahaya. Yang perlu diperhatikan adalah makna transenden dari agama. Agama bisa mengalami degradasi. Ia tidak selalu baik. Ia bisa saja sangat buruk. Lalu apakah agama masih relevan dengan persoalan kontemporer dalam hidup kita di zaman ini? Apakah agama masih layak kita ‘pertahankan’ jika tanda-tanda pembusukan di atas mulai terlihat? Apakah agama masih penting buat kita? Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut memang terkesan menggugat dan provokatif. Tapi pada kenyataannya – diakui atau tidak – dengan semakin canggihnya teknologi dan tingkat aktivitas yang tinggi, kita mulai terasa kehilangan makna spiritualitas dalam hidup. Bahkan mungkin dalam keberagamaan kita. Namun demikian, agama juga masih diyakini sebagai solusi segala permasalahan hidup, meski kadang terkesan naïf atau hanya menyentuh ‘kulit’. Hanya sekedar pelengkap, aksesoris. Keith Ward (Is Religion Dangerous?) menyatakan bahwa meski agama bukan dan tak bisa menjadi sumber kejahatan, tetapi para penganutnya memungkinkan menjadikan agama itu sendiri ‘berwajah’ tak ramah. Pada kenyataannya, konflik antar agama tidaklah murni karena agama semata. Ada kelindan kepentingan politik, ekonomi, budaya, sosial, dan hal lainnya yang merusak dan merasuki agama, sehingga agama menjadi gersang dan garang.
Yesus, Agama dan Paradigma Baru
Anjuran Albert Einstein perlu kita cermati, bahwa “Problem-problem signifikan yang kita hadapi tak dapat kita selesaikan pada level pemikiran yang sama seperti ketika dahulu kita menciptakannya”. Artinya kita membutuhkan paradigma baru yang dapat membantu kita memahami dan menghayati hidup dalam konteks yang plural. Dan peristiwa ‘membuka paradigma baru’ itu pun pernah dipraktikkan oleh seorang tukang kayu dari Nazaret, di wilayah Palestina, sekitar dua milenium yang lalu. Siapa lagi kalau bukan Yesus yang ditemani oleh 12 murid utama serta puluhan murid lainnya. Dialah ‘pelanggar hukum’ Yudaisme yang membuat gelisah para imam dan ahli Taurat Yahudi di masa itu.
 Yesus ‘gerah’ dengan ritual agama yang kehilangan makna (Matius 15:1-20). Yesus mengecam rutinitas ibadat yang hanya berbasiskan kepongahan rohani (Lukas 18: 9-14; Yohanes 8:2-11). Yesus marah pada para pemimpin agama yang hanya gila hormat dan membuat umat mentok spiritualitasnya (Matius 23:1-36). Yesus mengkritik dogma agama yang abai terhadap realitas kebutuhan umat manusia (Lukas 9:13; 13:10-17; 14:1-6). Yesus bahkan meminta agar setiap individu berperan aktif-positif dalam kehidupannya (Matius 5:13-16). Kita yang harus memberi makan mereka yang lapar, memberi minum yang haus, membebaskan orang-orang dari belenggu, memberi pakaian mereka yang telanjang, melawat mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang terpenjara, memberi tumpangan pada mereka yang terasing (Matius 25:35-36). Dan kita harus meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dalam bingkai paradigma bahwa kita adalah sesama umat manusia (Matius 7:12; Lukas 10:25-37). Yesus juga mengajarkan bahwa beriman kepada Allah identik dengan mengasihi sesama di lingkungan terdekat. Tanpa melihat perbedaan agama, status sosial, suku, ras, dsb.
Yesus ‘gerah’ dengan ritual agama yang kehilangan makna (Matius 15:1-20). Yesus mengecam rutinitas ibadat yang hanya berbasiskan kepongahan rohani (Lukas 18: 9-14; Yohanes 8:2-11). Yesus marah pada para pemimpin agama yang hanya gila hormat dan membuat umat mentok spiritualitasnya (Matius 23:1-36). Yesus mengkritik dogma agama yang abai terhadap realitas kebutuhan umat manusia (Lukas 9:13; 13:10-17; 14:1-6). Yesus bahkan meminta agar setiap individu berperan aktif-positif dalam kehidupannya (Matius 5:13-16). Kita yang harus memberi makan mereka yang lapar, memberi minum yang haus, membebaskan orang-orang dari belenggu, memberi pakaian mereka yang telanjang, melawat mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang terpenjara, memberi tumpangan pada mereka yang terasing (Matius 25:35-36). Dan kita harus meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dalam bingkai paradigma bahwa kita adalah sesama umat manusia (Matius 7:12; Lukas 10:25-37). Yesus juga mengajarkan bahwa beriman kepada Allah identik dengan mengasihi sesama di lingkungan terdekat. Tanpa melihat perbedaan agama, status sosial, suku, ras, dsb.Berdasarkan Alkitab, kita tahu, Yesus tak berupaya menggagas sebuah agama baru. Ia tak mengajak para murid-Nya menyingkirkan dan menghapus Yudaisme. Yang Ia ubah adalah paradigma umat beragama dalam praktik keberagamaan. Karena paradigma yang picik dan sempit dalam menginterpretasikan Kitab Suci, mempengaruhi perilaku kita dalam berelasi dengan sesama manusia. Juga akan menjadi cerminan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan.
Bahwa kegelapan adalah karena ketiadaan terang. Maka Yesus menunjuk setiap kita sebagai terang dunia. Dan bahwa garam adalah bagian ‘penting’ (meski hanya secuil) di tiap dapur keluarga, sekaligus bahan pencegah pembusukan. Maka setiap kita adalah garam dunia. Setiap manusia adalah terang dan garam dunia. Di dunia ini, dalam konteks kekinian. Jika demikian, apakah kita telah menjalankan fungsi keduanya, atau kita meredup dan tawar?
Benar bahwa Tuhan tidak berubah - dulu, kini dan selamanya. Namun, apa jadinya jika institusi keagamaan dan umat beragama tak pernah berubah, gagap dan panik dalam menyikapi tantangan dan persoalan dunia? Jika Tuhan hanya dijadikan pelarian kemalasan kita untuk berubah (metamorphosis) seperti diingatkan oleh Paulus dalam Roma 12:2, untuk apa kita meyakini adanya Tuhan dan menyembah-Nya? Di tengah-tengah bencana yang mendera bangsa kita, dan ribuan korban yang terperangkap rasa ‘gelap’ dan ‘tawar hati’ dalam melanjutkan babak kehidupan selanjutnya, apakah kita pun meredup dan mulai menjadi tawar? Ingatlah, bahwa agama bisa membusuk!
Bandung, 28 Okt 2010
(Dibuat untuk artikel Kolom Bina pada Warta jemaat GKI MY, 7 Nop 2010)
Dommy Waas